8 Fragmen Kucing Jalanan
; Sasti Gotama (Si Kucing yang Sangat Anjing)
(Penculikan)
Truk ini membawaku entah ke mana. Tak jelas apa yang diinginkan orang-orang bermasker saat mengambilku di sebuah pasar kota Labubu. Saat itu aku sedang bersiap memakan seekor pindang yang sempat kucuri dari pedagang ikan yang hendak pulang. Memang tidak bisa membuat kenyang sangat, tapi cukup untuk jadi kudapan sebelum kembali mengikat perut beberapa hari ke depan.
Saat orang-orang itu datang, bunyi sepatu boot mereka bergema seperti alarm kebakaran. Instingku mengatakan mereka orang berbahaya. Aku berusaha melawan. Tapi mereka terlalu kuat.
Pada akhirnya nasib yang lemah adalah kalah. Orang-orang itu memasukkanku ke kerangkeng besi. Lalu semua berjalan dalam rentang yang terasa begitu singkat. Kerangkengku terdampar di truk ini, bersama puluhan kerangkeng lain, entah ke mana.
(Labubu: Seorang anak dan sebungkus roti)
Anak itu seperti orang baru di sini. Dia berjalan sendiri seolah tak punya teman. Tapi tentu aku berbeda dengannya. Dia sendiri karena dia lemah. Aku sendiri karena kuat. Aku preman jalanan, sosok yang ditakuti para kucing tunawiswa, bahkan penjual ikan. Sekadar bertemu denganku mereka segan.
Namun hari ini aku malas makan pindang, atau cakalang. Aku ingin sesuatu yang baru. Misalnya, roti di tangan anak itu, yang bundar, dan kecoklatan. Aku teringat pada steik yang pernah ditonton Badar. Ingatan masa kecilku masih merekam jelas bagaimana di kotak yang Badar sebut televisi, liur orang yang terjebak di dalamnya mencair. Susah payah orang itu hendak memasukkan kembali liur ke mulutnya yang berkedut.
Setelah beberapa saat, orang itu memotong steik. Potongan kecilnya ia ambil dengan garpu, dan nyam nyam. Aku ikut ngiler melihatnya. Badar tertawa. Ia berjanji akan membawakanku steik di kemudian hari. Tentu saja janji itu tak pernah ditepati, sebab ia tak pernah kembali setelah wajahnya diculik kotak lain yang oleh orang disebut figura.
Berbekal penasaran akan steik yang kian perdu, kuterkam kaki kiri anak itu yang tak memakai kaos kaki. “Anjing!” Hei, aku kucing bukan anjing, batinku. Aku menggeram. Apa susahnya bagi manusia merelakan sebungkus roti bagi makhluk yang dalam sehari belum tentu bisa makan barang pindang seekor? Anak itu tak beda dengan manusia lain, sama jahat. Hanya Badar yang baik seorang.
Wajah anak itu datar seperti menimbang sesuatu. Apa dia akan memberikan roti itu padaku? Aku berjanji akan menyebutnya manusia baik, seperti Badar. Tangan anak itu terangkat, lalu roti itu terlepas dari tangannya. Melayang, dan selesai. Roti itu jatuh ke comberan. Anak itu lanjut pergi, sambil mencibir sedikit. Meoong, anjing kau.
(Dari awal, segalanya penuh luka)
Saat rembulan paripurna, di tengah ngeong dua kucing beradu suara, ibu membawaku melihat dunia yang katanya seperti taman bermain. Ini kali ketujuh ibu membawa anak-anak tumbuh, dan seperti sebelumnya, tiada kesulitan berarti dalam persalinan.
Hariku dipenuhi tetes cairan susu, bising tawar-menawar, juga amis ikan. Hingga saat mataku terbuka kali pertama, yang kulihat adalah tubuh ibu yang kaku dan sedikit biru. Ketika cahaya oranye kutangkap dan monster-monster besar yang setelahnya kutahu adalah manusia datang, sosok ibu terangkat dan tak lagi begitu dekat.
Aku berjalan mencari ibu dan terus berjalan. Cairan susunya begitu candu. Aku ingin bertemu ibu.
(Kucing-kucing tanpa sembilan nyawa)
Selama penculikan, aku dekat dengan kucing yang mengaku bernama Pupu. Aku tertawa. Geli rasanya ada kucing memiliki nama manusia. “Namaku diberikan oleh babuku, jangan tertawa, dia baik sekali.”
“Kalau dia baik, takkan kau berakhir di gudang usang ini.”
“Dia benar-benar baik. Aku ingin bertemu dengannya lagi. Hanya saja ibunya seperti orang sinting. Aku takut melihatnya.”
Begitulah, selepas truk yang mengangkutku berhenti, para kucing korban penculikan ditaruh ke dalam gudang usang. Di sana, aku menghabiskan waktu bercengkrama dengan Pupu, yang ternyata menyenangkan juga. Yah, walau demikian aku sebenarnya waswas. Gudang ini bau amis darah, juga bau bangkai. Aku takut. Bau ibu yang membiru telah membekas sebagai titik hitam dalam ingatan.
Tak lama, orang-orang bermasker itu datang dan mengeluarkan satu per satu kucing dari kerangkeng, membawanya ke ruangan sebelah. Sialnya, perasaan waswas makin menggila. Teriakan kucing terdengar tiap beberapa detik.
Semakin banyak kucing diambil, dibawa ke ruang sebelah. Teriakan-teriakan terdengar, sarat sakit dan takut, gigilkanku, hingga bulu sekujur tubuh teracung serupa jarum.
Oh tidak, ini penjagalan. Aku teringat ikan-ikan besar di pasar yang sering kuintai namun tak pernah kudapatkan. Saat ada manusia mengeluarkan kertas merah atau biru, lalu menunjuk salah satu ikan besar itu, tak lama sebuah golok tajam dan mengkilat akan memantulkan gambar seekor ikan putus kepalanya di mataku. Apakah kucing-kucing itu bernasib sama seperti ikan besar di pasar?
“Pupu, kalau orang-orang itu datang dan mengambilmu, segera kau gigit tangan mereka sekuat-kuatnya, lalu lari, jangan berpaling.” Bulu-bulu Pupu teracung sempurna. Dia paham maksudku.
Benar saja, giliran Pupu tiba. Aku menggeram menunjukkan permusuhan. “Oh, lucu sekali kucing ini.” Salah seorang bermasker tertawa melihatku. Tangannya terjulur ke dalam kerangkeng Pupu, mengeluarkannya dari dalam.
“Pupu, sekarang.”
(Taman Bermain)
Masa kecilku terselamatkan berkat Badar. Setelah para manusia mengangkat ibu entah ke mana, kaki membawaku ke mana pun kulihat manusia. Kuikuti mereka, walau lapar dan belum minum susu, sebab barangkali mereka bisa menjawab pertanyaanku; di mana ibu?
Lama kelamaan tubuhku hilang daya dan tenggorokanku jadi kering. Beruntung, Badar menemukanku. Dia juru selamat. Taman bermain yang ditawarkan ibu dulu, kini kutemukan di hangat rengkuhnya. Bersamanya aku bermain kejar-kejaran, gigit-gigitan, petak umpet, dan banyak lagi.
Sampai saat aku berumur setahun—mungkin saja demikian, sebab sehari sebelumnya Badar membelikanku sekaleng Whiskas basah sambil berkata; ini ulang tahunmu, sudah setahun sejak kau bersamaku—semua kembali seperti semula. Siang itu aku yang rebahan karena kenyang, dikejutkan oleh kedatangan beberapa teman Badar. Anehnya mereka berteriak dan menangis, padahal Badar sedang pulas di sampingku. Kutoel-toel wajahnya, dia sedikit biru. Aku jadi teringat ibu.
Selepas itu, Badar juga hilang. Para manusia mengangkatnya sebagaimana mereka dahulu mengangkat ibu. Baru kutahu bahwa kegiatan itu adalah penculikan, sebab semua yang terangkat tak pernah kembali. Saat beberapa manusia lain datang beberapa hari kemudian, kulihat wajah Badar ada di pelukan sebuah kotak. Aku ingin menghampirinya, tapi manusia-manusia itu mengusirku dan tak pernah membiarkanku bisa bertemu dengannya.
(Saiba: Anak itu lagi)
Malam itu aku berhasil kabur. Sendiri. Pupu, aku tak tahu bagaimana nasibnya. Dia tidak berhasil kabur, dan walau kudengar teriakannya dari ruang sebelah, kuharap dia masih hidup. Barangkali dia hanya diusili sebentar sebelum kemudian dimasukkan ke taman bermain indah. Ya, barangkali begitu.
Pagi menyapa, aku berjalan di kota yang sama sekali baru. Perutku berbunyi nyaring. Ah, seekor pindang di pasar Labubu. Susah payah kucuri sampai harus rela disiram air amis, ujungnya tak sempat kumakan juga.
Langkahku membawa ke tepian parit bau bacin. Anehnya, di sana kutemui si anak songong pelempar roti ke comberan. Pindah juga dia ternyata, apakah dia diculik juga? batinku. Seperti di Labubu, ia juga membawa roti. Aku teringat steik kembali. Perutku berbunyi.
Melihat gelagatnya, aku tahu apa yang bakal dia lakukan. Tangannya terangkat, roti melayang. Aku melompat, hap, roti kusambar. Tapi oh Tuhan, aku tergelincir masuk parit. Lagi-lagi anjing, batinku.
Anak itu menyumpahi. Katanya aku dungu. Tapi ia menghampiriku yang cemong berbalur lumpur, dan melemparkanku ke hampar rumput. Tangannya kini ikut kotor. Dia berlalu, sambil membawa hatiku. Setelah sekian lama, kutemukan lagi manusia baik selain Badar. Ah, mungkin dia orang ketiga setelah Badar dan babu si Pupu.
(Semua manusia jahat. Tentu selain Badar)
Rumah Badar benar-benar tidak lagi memiliki pintu. Aku kini tunawisma yang kehilangan taman bermain. Sempat terpikir mencari ibu, tapi belum tentu bakal ketemu, dan jika ketemu, barangkali dia sudah memiliki keluarga baru, anak-anak baru, yang lebih lucu dariku.
Maka kisahku sebagai preman jalanan terpaksa dimulai. Dari awalnya malu-malu meminta sampai akhirnya beringas mencuri, atau dari awalnya sering diajak seteru kucing-kucing sok jagoan, sampai jadi preman pasar, semua kulalui. Bersama itu, kulewati pula masa saat sering ditimpuk batu oleh para pedagang, disiram air comberan, disabet pisau tajam sampai berbekas codet melintang di dahi dan sekujur badan. Di mataku, dunia tumbuh sebagai neraka, dan manusia penghuninya. Tentu saja kecuali Badar.
(Kadal gemuk; hadiah untuk anak itu)
Kejadian terakhir menyadarkan bahwa anak itu masih tergolong baik. Walau sebelumnya seperti anjing, dia mau mengambilku dari comberan, dan mengorbankan kebersihan tangannya. Kebaikannya patut diberi ganjaran.
Di mulutku, seekor kadal gemuk pasrah menerima takdirnya. Setelah aksi kejar-kejaran cukup melelahkan, ia angkat tangan, dan bersedia menjadi seserahan untuk anak itu.
Dengan langkah riang aku pergi ke rumah anak itu yang letaknya sudah kuhafal betul setelah kemarin kubuntuti dia diam-diam. Aku menaiki pohon, hendak loncat ke jendela rumahnya.
“Jadi nanti kau tinggal dengannya. Jadi nanti kalian bahagia. Tapi aku sendiri. Aku tak ingin dia bahagia. Seharusnya dia menderita, sama denganku.” Seorang wanita paruh baya seperti orang sinting berbicara dengan anak itu. Di tangannya, sebilah pisau diarahkan ke leher si anak.
Apakah dia ibunya? Tapi dia seperti psikopat. Seorang ibu tidak mungkin seperti itu. Ibuku saja baik, walau ia hilang dan tak kunjung balik. Aku teringat perkataan si Pupu, bahwa babunya memiliki ibu sinting.
Aku mengeong, lebih tepatnya menggeram, lalu lompat ke jendela dan lanjut menimpuk tubuh si wanita paruh baya. Rasakan, tubuh kurusku yang penuh tulang pasti cukup sakit baginya. Wanita itu terjatuh, meraung, sementara pisaunya jatuh berdenting.
Aku keluar lagi, menoleh. Anak itu ikut keluar, memandangku. Kuletakkan kadal gemuk yang sedikit syok, lalu meloncat ke sesemakan. Selamat tinggal, babu Pupu.
Sumenep, 2025
NB: Tulisan ini ditulis menggunakan teknik fraksionasi ala Pak Ranang Aji SP. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjadi sudut pandang lain, serta apresiasi bagi cerpen Sasti Gotama (Si Kucing yang Sangat Anjing/Jawa Pos (12/04/2025).
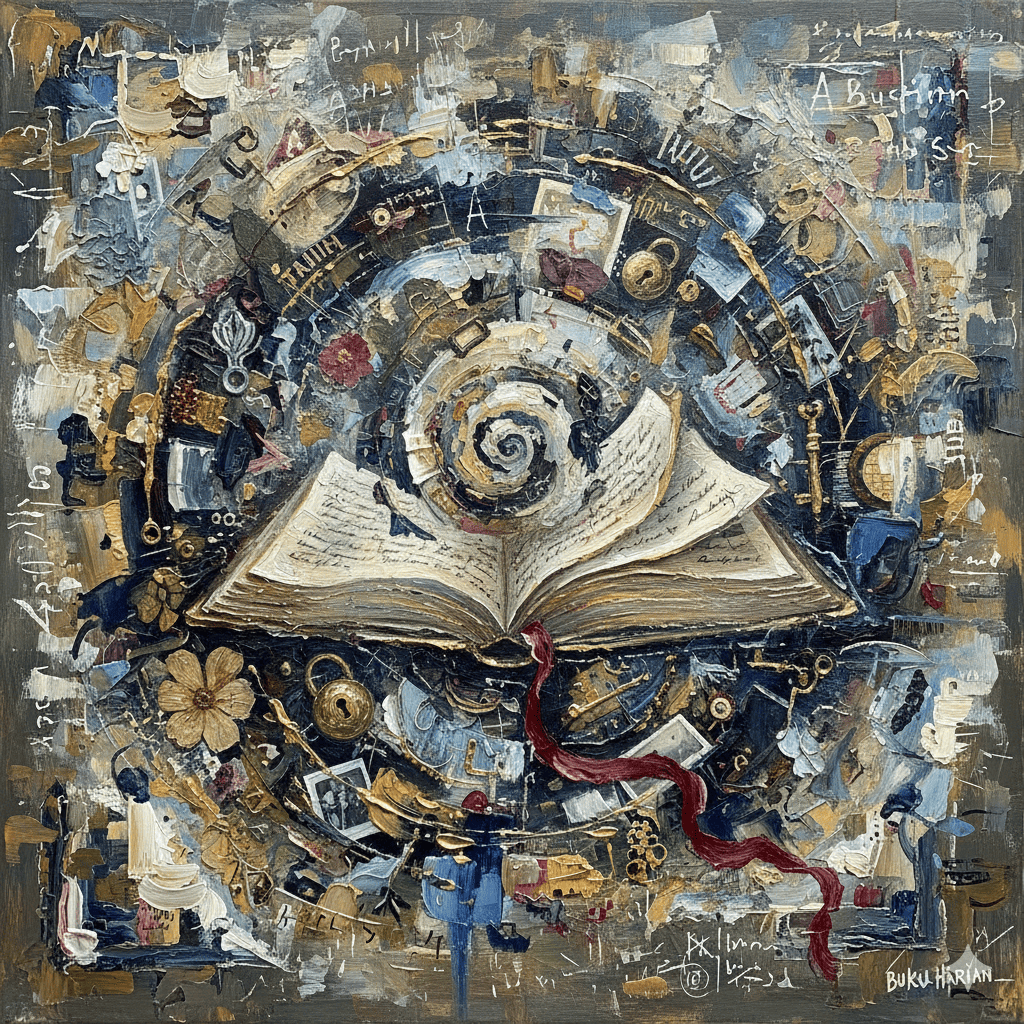

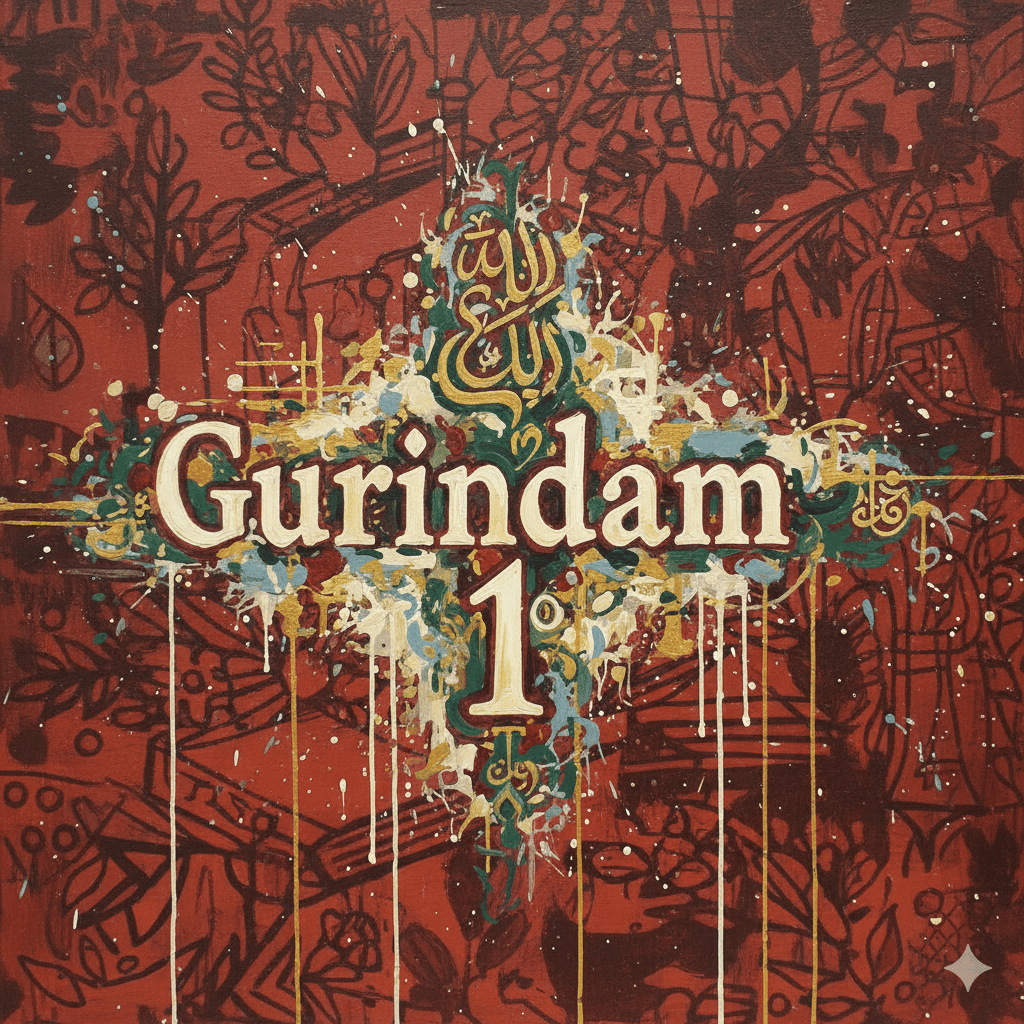
Comments
Sign in with Google to leave a comment
No comments yet. Be the first to share your thoughts!